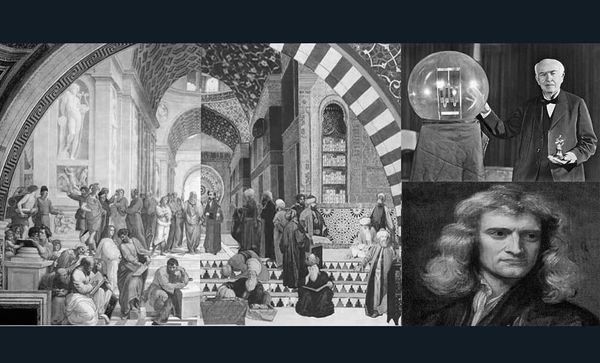Dengan munculnya kekhilafahan Utsmani, tampuk kepemimpinan umat Islam tidak lagi dipegang oleh keturunan Quraisy
Meski awalnya berjalan normal, menjelang keruntuhan Khilafah, bibit bibit perpecahan umat Islam akibat munculnya nasionalisme golongan Turki dan golongan Arab dimunculkan oleh musuh musuh Islam yang menjadi salah satu faktor atas hancurnya Khilafah dari dalam
Lantas, bolehkah Khalifah berasal dari keturunan selain Quraisy?
Untuk mengetahui hal tersebut, yuk disimak artikel terbaru dari @komunitasliterasiislam. Selamat membaca 😁
Bagaimana dengan status Khilāfah yang disandang dinasti ‘Uṡmānī, sedangkan mereka bukan berasal dari silsilah Quraisy?
Sebagian besar ulama yang menulis kitab-kitab fiqh siyāsah (fiqh politik) memasukkan syarat Quraisy sebagai pra-syarat kepemimpinan Khalīfah, berdasarkan pada hadis Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam,
“Sesungguhnya kepemimpinan ini berada di Quraisy, tidaklah seseorang memusuhi mereka, kecuali Allah yang menelungkupkannya dalam neraka di atas wajahnya, selama mereka (orang Quraisy) menegakkan agama.” (inna haża al-amra fī Quraisyin lā yu’ādīhim ahadun illā kabbahullāhu fī al-nār ‘alā wajhih mā aqāmū al-dīn),
Selain pra-syarat kedudukan Khalīfah yang lain seperti harus laki-laki, mencapai usia baligh, berpengetahuan, adil, mampu, dan tidak cacat fisik.
Kala itu, perkara ini menjadi perkara utama yang diperdebatkan, dan mulai diramaikan kembali di masa kolonial ketika Inggris dan Prancis berusaha menghapuskan kepemimpinan ‘Uṡmānī atas dunia Islam melalui hasutan kepada para Nasionalis Arab untuk melakukan berbagai pemberontakan di akhir abad ke-19.
Isu ini pertama kali dibawa oleh Louis Sabūnjī, seorang Katolik Suriah yang bermukim di London, yang menerbitkan surat kabar al-Khalifa dimana di dalamnya ia menyatakan bahwa gelar Khalīfah yang disandang dinasti ‘Uṡmānī hanyalah fiksi belaka.
Isu ini juga diramaikan oleh para intelektual Mesir semacam ‘Abd al-Raḥmān al-Kawākibī dan Rasyīd Riḍā yang mengusung ide “Khilāfah Arab”.
Lütfi Pasha yang merupakan sejarawan ‘Uṡmānī sekaligus Vezir-i (Wazir) Azam (Wakil Khalīfah) di masa Sultan Süleyman I, menyelesaikan masalah legitimasi silsilah Quraisy ini dengan mengatakan bahwa apabila penguasa menggabungkan antara dirinya dengan prinsip-prinsip keimanan dan keadilan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan sifat-sifat kepemimpinan lain yang umum; maka dialah seorang Sultan yang dapat mengklaim gelar Imam, Khalīfah, Walī, dan Amīr tanpa kontradiksi.
Di antara ulama-ulama terdahulu yang berpendapat bahwa silsilah Quraisy adalah elemen yang esensial dalam teori politik Sunni, namun bukan termasuk syarat utama jabatan Khalīfah adalah al-Jurjāni, al-Bāqillānī, dan Ibn Khaldūn.
Menurut mereka, hadis tentang kepemimpinan Quraisy hanya berlaku di masa Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan Khulafā’ al-Rāsyidīn, dan setelah masa itu hadis tersebut tidak lagi bisa diaplikasikan.
Dalam analisa Ibn Khaldūn, lambat laun kekuasaan kaum Quraisy melemah.
Solidaritas (‘aṣabiyyah) mereka lenyap sebagai akibat hidup mewah dan berlebih, dan sebagai akibat dari kenyataan yang ada, bahwa berbagai macam negara di seluruh penjuru dunia telah memanfaatkan mereka.
Dengan demikian, mereka sudah terlalu lemah untuk dapat melaksanakan kewajiban Khilāfah. Bangsa-bangsa non-Arab pun menaklukkan mereka, dan merebut kekuasaan eksekutif.
Sebenarnya, Ibn Khaldūn tetap mengakui pra-syarat silsilah Quraisy sebagai Khalīfah, namun berkaca dari realitas pada masanya, ia lebih memilih untuk melihat dari esensi dibuatnya syariat itu sendiri (‘illat).
Ibn Khaldūn berargumen,
“Apabila kita telaah hikmah dari dijadikannya keturunan Quraisy sebagai pra-syarat dalam Imāmah (Khilāfah), dan tujuan yang dimaksud oleh al-Syāri’ (Pemberi Syariat, yakni Allah dan Rasul-Nya) dari pra-syarat tersebut, kita akan tahu bahwa di balik itu tidak semata terkandung berwasilah dengan Nabi, seperti yang dikatakan banyak orang. Wasilah (hubungan keturunan dengan Nabi) memang ada jika jelas seseorang berasal dari keturunan Quraisy, sebab Nabi sendiri berasal dari keturunan itu. Wasilah demikian merupakan tabarruk (mencari berkah, bagi orang yang punya wasilah demikian). Namun, seperti diketahui, tabarruk bukanlah tujuan syariat. Jika keturunan tertentu dijadikan pra-syarat Imāmah, tentunya harus ada maslahat umum di balik tujuan penetapan demikian.
Namun, apabila persoalan itu kita telaah dan kita analisa, kita akan mendapatkan bahwa maslahat umum dimaksud tidak lain diungkapkan dalam solidaritas sosial (‘aṣabiyyah) yang dimiliki para imam keturunan Arab. Solidaritas itu memberikan perlindungan dan tuntutan, serta dapat melepaskan sang imam dari oposisi dan perpecahan. Agama dan pemeluknya tentu akan dapat menerima dia beserta keluarganya, dan dia pun dapat mengadakan hubungan yang akrab dengan mereka.”
Solidaritas tersebut (karena ia berasal dari keturunan Quraisy) dapat meningkatkan kewibaan Khalifah, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan mengurangi kemungkinan timbulnya perpecahan umat Islam.
Dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama yang tidak menjadikan silsilah Quraisy sebagai pra-syarat dalam jabatan Khalīfah, maka semenjak masa Selim I, para penguasa ‘Uṡmānī sampai keruntuhan mereka di tahun 1924 digelari “Khalīfah yang Agung” (Halife-i Uzma) dalam berbagai dokumen resminya, dan meminta kepada para penguasa Muslim di belahan bumi lain untuk mengakui mereka sebagai Khalīfah yang sebenarnya untuk dunia Islam.
Wallahu’alam bis Shawab. []
Visualis : Muhammad Afifuddin Al Fakkar
Sumber:
Abū ‘Abd ‘Allah Muḥammad b. Ismā’īl b. Ibrāhīm al-Bukhārī. Ṣaḥīh al-Bukhārī (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2009).
Alima Bissenove. Ottomanism, Pan-Islamism, and the Caliphate Discourse at the Turn of the 20th Century. Barqiyya Vol 9 No. 1 (Februari 2004).
Nurullah Ardic. Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun Between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate. Journal of Near Eastern Studies Vol. 71 No. 2 (Oktober 2012).
Ibn Khaldūn, Muqaddimah, Penerjemah Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
Thomas W. Arnold. The Caliphate. (Oxford:The Clarendon Press, 1924).